MEDIA mengemas citra Sherly Tjoanda dengan label “gubernur cantik” yang identik dengan sapaan ramah khasnya: “ayo sini kita foto bareng”. Gaya ini kemudian direproduksi, diunggah ulang, dan dipoles melalui akun Tiktok miliknya. Persepsi publik kemudian terbentuk: sang gubernur adalah pemimpin yang dekat, melayani, dan dicintai rakyat.
Bukan hanya warga Maluku Utara yang terkesima, warganet dari berbagai daerah ikut-ikutan terpukau dengan cara berkuasa “ibu gub” ini. Kalau periksa komentar-komentar unggahan video di tiktok, hampir seluruhnya bernada pujian–entahlah. Fenomena ini bisa jadi menunjukkan bahwa publik menikmati kinerja para pemimpin lewat online, lewat ponsel–kadang sambil rebahan, diukur dari keramahan depan kamera, bukan dari kebijakan yang dijalankan.
Sherly tampaknya paling lihai memainkan peran ini: memoles citra dengan paras yang menawan, turut yang sopan, dan gestur yang seolah-olah mengayomi masyarakat. Video-video “ibu gub” ini bukan sekadar mendulang like, tetapi juga empati dan seperti menebar harapan. Hingga para netizen dikelabui dengan konten-konten, algoritmanya melintasi pulau-pulau. “Ibu gub” bahkan wara-wiri di podcast dan stasiun televisi.
Jean Baudrillard dalam teorinya Simulacra and Simulation, menyatakan bahwa hiperrealitas, dimana tanda dan simbol tidak lagi merepresentasikan realitas, tetapi menggantikannya. Realitas, menurut sosiolog politik asal Prancis itu, bukan lagi pijakan utama, yang ada hanyalah representasi yang terus menerus menyalin dirinya sendiri hingga kehilangan makna aslinya.
Dengan kata lain, kepemimpinan sekadar menjadi panggung, bukan pengabdian, dan rakyat? Hanya jadi penonton yang dibius dengan citra. Fenomena “gubernur cantik” dan “ayo sini kita foto bareng” inilah disebut simulakra politik. Bukan asli, tetapi imitasi, barang palsu.
Representasi ini seolah-olah lebih nyata di mata publik ketimbang realitas sosial yang terjadi di Maluku Utara saat ini, dimana konflik akibat proyek “hilirisasi nikel” terjadi di banyak tempat, dan banyak pula memakan korban. Rakyat terhipnotis oleh hyperreality yang Sherly umbar di Tiktok dan media sosial, sehingga menutupi kenyataan ‘bencana hilirisasi’ dari jadi mantra program strategis nasional pemerintah di kepulauan ini.
Mantra program strategis nasional atau PSN ini–yang sekarang dilanjutkan pemerintahan Prabowo-Gibran, juga didukung oleh Sherly–telah menetapkan beberapa wilayah Maluku Utara sebagai pusat pertumbuhan kawasan industri: di Buli Halmahera Timur, di Weda Halmahera Tengah, dan di Pulau Obi Halmahera Selatan.
Hilirisasi ini diklaim demi kesejahteraan, yang sayangnya itu pun hanyalah ilusi. Sebab, di balik klaim itu, ada banyak warga di berbagai tempat menghadapi realitas menyakitkan. Lahan perkebunan dijual paksa, sumber-sumber kehidupan seperti sungai dicemari limbah tambang, hutan digunduli, udara disesaki debu batubara, dan ikan-ikan di laut dicemari merkuri dan arsenik, dan warganya diintimidasi seperti kasus Maba Sangaji.
Masalah-masalah ini dibiarkan begitu saja, sebab, yang jadi fokus dari cerita hilirisasi nikel bukan rusaknya sumber kehidupan warga, tetapi besaran pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan negara dan gubernur dengan wajah oligarki ini. Di sisi lain, kualitas pendidikan di pedesaan di Maluku Utara yang masih jauh panggang dari api. Kualitasnya hanya terpusat di perkotaan adalah bukti bahwa sosok pujaan warganet ini belum memainkan peran strategis sebagai pelayan rakyat.
Sebagai gubernur yang kerap menyamakan mengatur daerah sama dengan halnya mengurus rumah tangga, mestinya bisa peka terhadap penderitaan warganya: ada perempuan yang kehilangan suami, anak, dan atau ayah karena mereka di penjara setelah mempertahankan hutan adat, tanah, dan ruang masa depan generasi selanjutnya.
Tetapi, ketika “ibu gub” ini berkata “kita harus menjaga iklim investasi”, seperti memberi pesan bahwa dia berpihak sepenuhnya pada pertambangan meski harus mengorbankan nasib warganya. Sherly membungkam mulutnya ketika ada sebelas warga yang mati-matian mempertaruhkan hidupnya, ia justru sibuk menebar citra, seolah-olah kehidupan warga di Maluku Utara baik-baik saja.
Sikap diam Sherly mengingatkan pada konsep alienasi Erich Fromm: ibarat sebuah patung yang memiliki mata tetapi tidak melihat, memiliki telinga tetapi tidak bisa mendengar. Pertanyaannya, apakah jabatan gubernur memiliki kesamaan dengan patung yang digambarkan Fromm?
Semoga saja tidak, karena jika benar sama dengan patung, maka seluruh masyarakat Maluku Utara sejatinya sedang kembali ke masa lalu, zaman animisme dan dinamisme, dipimpin oleh patung dan simbol, bukan oleh kepedulian atas penderitaan rakyatnya. Atau kalau kita kembali ke masa prasejarah, artinya kita dipimpin oleh kekuatan gaib: kebijakannya tidak tampak, tetapi citranya di pertunjukan dari balik layar kaca yang seolah-olah menjadi titik realitas itu sendiri.[]
Ummulkhairy M. Dun adalah seorang mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

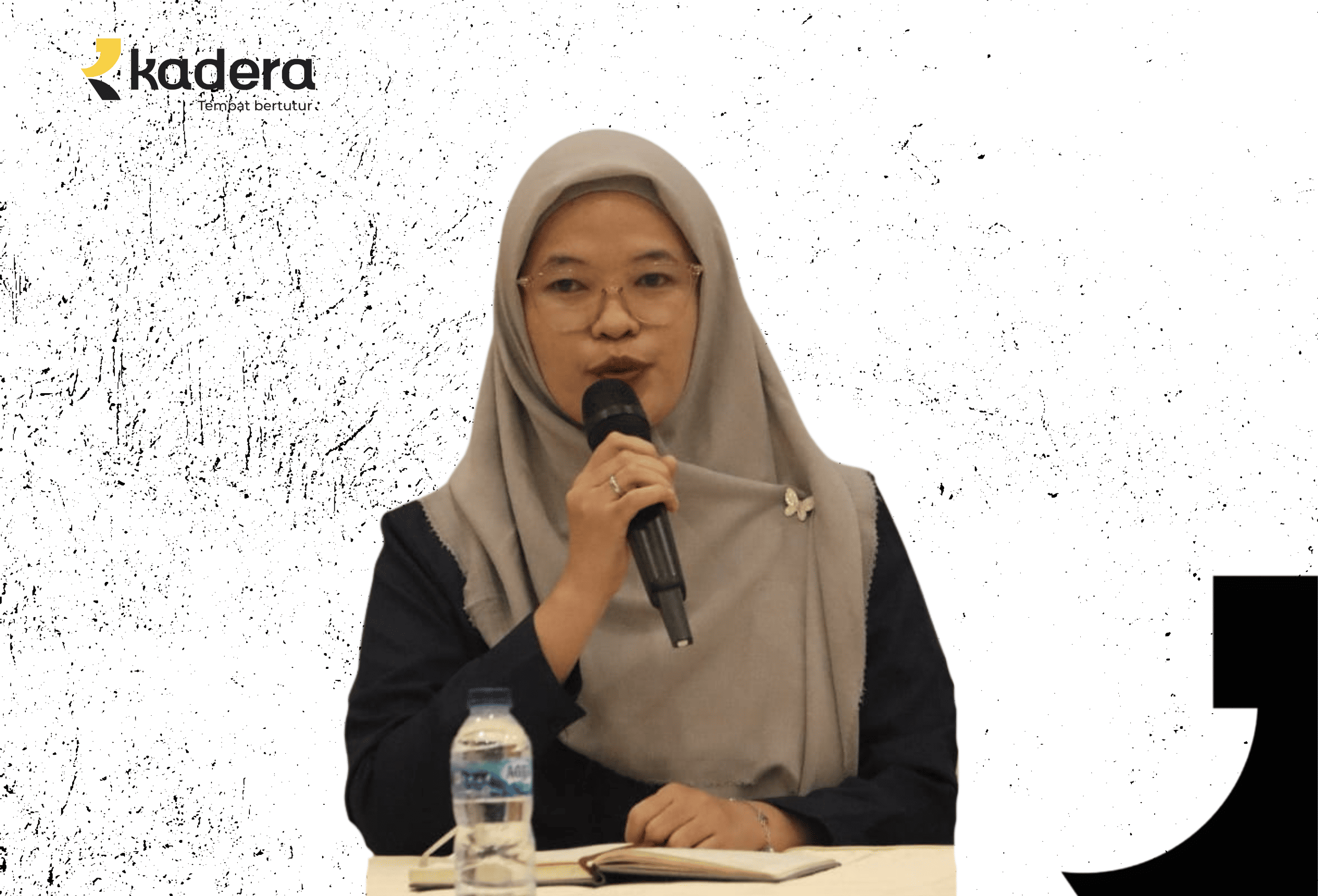
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.