DI rumah rakyat, beberapa hari yang lalu, orang-orang yang berjas dan berkebaya itu berjoget. Konon, mereka mendapat hiburan setelah pidato Prabowo Subianto. Pidato yang mendapat pujian dan tepuk tangan dari penggemar. Sambutan lanjutan adalah joget, yang mengartikan kegembiraan atau kepuasan.
Tayangan mereka ditonton jutaan orang di seantero Indonesia. Ada yang menanggapinya dengan tersenyum dicampuri sinis. Ada yang bingung dan penasaran menebak agenda berjoget dalam kepentingan kaum legislatif. Ada yang marah-marah dan kecewa mengetahui orang-orang yang terhormat malah berjoget. Bagaimana hubungan berjoget dan demokrasi di Indonesia? Pertanyaan yang mungkin salah, yang boleh tidak dijawab.
Pada situasi yang lain, lelaki menghuni gedung parlemen menasihati dan menantang rakyat bertajuk demokrasi. Ia mengingatkan dalam hak-hak berdemokrasi harus menggunakan “adat istiadat”. Kita tidak mengerti maksud “adat istiadat” dan demokrasi di Indonesia. Ia pun menyatakan masalah menggunakan diksi “bego” dan “tolol”. Jutaan orang yang melihatnya saat omong merasa terhina. Orang yang terhormat dan bergelimang harta itu terlihat sengaja mau bikin ribut.
Hari-hari yang bermasalah gara-gara kata terjadi di Indonesia. Kita masih bisa mendaftar kata-kata yang digunakan elite di birokrasi atau kaum terhormat di legislatif menimbulkan masalah sangat besar. Mereka mengucapkan di depan kamera. Kita menikmatinya dengan mendendam dan muak. Apa yang membuat kata-kata bergolak dalam nalar demokrasi Indonesia?
Pada hari yang berpetaka mengakibatkan kematian, pilihan kata menentukan benar dan salah. Kita memihak penyebutan terhadap kejadian mengenaskan adalah “dilindas”. Pihak sana dan para penggemar kekuasaan menyatakan “terlindas”. Kita bermasalah lagi dengan kata-kata berdasarkan kejadian, yang rekamannya cepat beredar ke ponsel di tangan jutaan orang. Kematian Affan Kurniawan (28 Agustus 2025) yang membarakan marah dan duka demokrasi.
Di Jakarta dan pelbagai kota, api menjadi bukti kemarahan rakyat. Polemik pun membesar berkaitan pihak-pihak melakukan demonstrasi, kerusuhan, dan penyelamatan. Indonesia dalam linglung. Indonesia sedang gawat. Indonesia berlakon petaka.
Kita mulai memikirkan tokoh-tokoh yang dianggap menimbulkan gegeran di Indonesia. Di kekuasaan dan kerja-kerja demi Indonesia, apakah mereka punya otak? Beberapa orang memilih menanyakan mengenai hati-nurani. Kita bukan yang menjawab meski mulai menyadari demokrasi tak berotak dan demokrasi tak bernurani diselenggarakan di Indonesia saat Prabowo Subianto belum setahun berkuasa.
Hari-hari yang rumit dan menyakitkan. Kita merenung dulu di hadapan puisi, selingan dari tayangan-tayangan demonstrasi yang bikin menangis dan merana. Puisi yang kita baca berjudul “Ciri-Ciri Orang Indonesia” gubahan Remy Sylado (1982). Kita membaca sambil mengingat Indonesia yang silam dan sekarang: Di sebuah ruang pameran genetika/ otak orang Cina dipuji sebab usianya setengah abad/ otak orang Barat dipuji sebab dipakai terus-menerus/ otak orang Indonesia dipuji sebab belum pernah dipakai.
Kita ingin menggunakan kutipan itu saat menyimak omongan orang-orang di legislatif dan kabinet. Mereka saat bicara berdandan rapi dan tampak pintar. Yang terjadi adalah rentetan malapetaka sambil kita malu-malu dan berbisik menuduh mereka justru tak berotak.
Indonesia yang memiliki sejuta masalah tidak dapat dijawab cuma lewat puisi. Kita membaca puisi untuk “memandingi” diksi-diksi yang bermunculan dalam berita dan komentar-komentar di media sosial.
Di hari-hari yang buruk, kita dipaksa memikirkan “minta maaf”. Tokoh-tokoh penting menyampaikan “minta maaf”. Mereka membuat rekaman yang serius dan politis agar rakyat mengetahui mereka benar-benar “minta maaf”. Kita tetap sulit paham mengenai demokrasi, kematian, dan “minta maaf”. Pada saat ruwet, bahasa Indonesia tidak memudahkan kita menuju terang tapi tetap saja terbelenggu dan terjebak dalam gelap. Setelah “minta maaf:, kita tetap gagal paham meski membuka selusin kamus mengenai pernyataan menggunakan diksi “kecewa”.
Yang membuat kita kaget adalah masalah kata-kata berlanjut dengan kedatangan Presiden RI dan Ketua DPR RI ke rumah duka, rumah dihuni korban di jalan demokrasi. Kamera-kamera menyorot demi mencipta pesan-pesan yang samar atau jelas mengenai Prabowo Subianto dan Puan Maharani atas situasi Indonesia. Kehadiran di rumah duka yang sederhana, berbeda dengan ingatan kita tentang rumah rakyat yang digunakan untuk berjoget. Kita sedang bermasalah rumah dan jalan-jalan yang digunakan untuk demonstrasi sekaligus pergelaran kekerasan.
Kita belum rampung memikirkan rumah rakyat dan rumah duka, terjadi penggerudukan dan perusakan rumah orang yang mulia di DPR RI. Rumah mewah itu menjadi sasaran massa yang marah, membawa bekal beberapa omongan tokoh dan disokong situasi demokrasi yang sedang puyeng: 30 Agustus 2025.
Yang agak berbeda adalah kedatangan sosok artis sekaligus sosok terhormat di DPR RI. Ia memilih mengunjungi kuburan, 29 Agustus 2025. Di situ, ia mengucapkan kata-kata di depan beberapa kamera. Sosok yang memilih mengenakan kaos dan topi. Ia berada di tempat yang membedakan pesan dengan tokoh-tokoh besar yang lain. Di kuburan, kata-kata untuk demokrasi dan kematian disampaikan bukan sebagai tandingan atas kata-kata para tokoh terucap di rumah duka.
Akhir pekan di Indonesia yang biasa mengenai senang, indah, nikmat, dan seru berganti kemarahan, ketakutan, kebingungan, kebencian, dan kenestapaan. Kita belum selesai dengan kata-kata dan tokoh-tokoh yang membuat petaka-petaka demokrasi di Indonesia.
Kita menanti hari-hari yang pulih dan terang sambil memikirkan peringatan Jakob Sumardjo (2009). Yang ditulis berkaitan masa lalu tapi kita bisa mengutip untuk masa sekarang: “Indonesia itu garis miring, sejak dulu kala. Indonesia selalu menolak ketegasan pilihan, vertikal atau horisontal. Indonesia berpikir dalam garis miringnya. Kalau dihadapkan pada pilihannya ambil ini atau ambil itu, memihak sini atau memihak sana, maka jawabannya miring. Ambil ini dan itu, memihak sini dan sana sekaligus.” Indonesia masa sekarang mungkin Indonesia garis miring saat demokrasi berantakan dan korban-korban bergelimpangan saat kaum arogan masih rajin omong dan memberi perintah-perintah.
Indonesia belum tenang, beres, dan girang. Demokrasi yang babak belur sulit disembuhkan. Kita mungkin meratapi semua sambil mendengarkan lagu-lagu asmara yang cengeng untuk pelarian. Namun, orang yang teguh mungkin memberi kuping untuk lagu-lagu Homicide. Kita mendapat kata-kata dalam seruan galak dan mencekam: opera sabun penyusun undang-undang pemilu/ yang mencoba membanyol tentang kekonyolan demokrasi/ yang rapi berdasi menopengi mutilasi/ pembebasan dengan sengkarut argumen basi/ tentang bagaimana menyamankan posisi. Kita diingatkan lagi situasi pelik haris ini bersumber hajatan demokrasi, sekian bulan yang lalu.
*Kabut merupakan nama pena dari seorang pengarsip, esais, dan kritikus sastra Indonesia

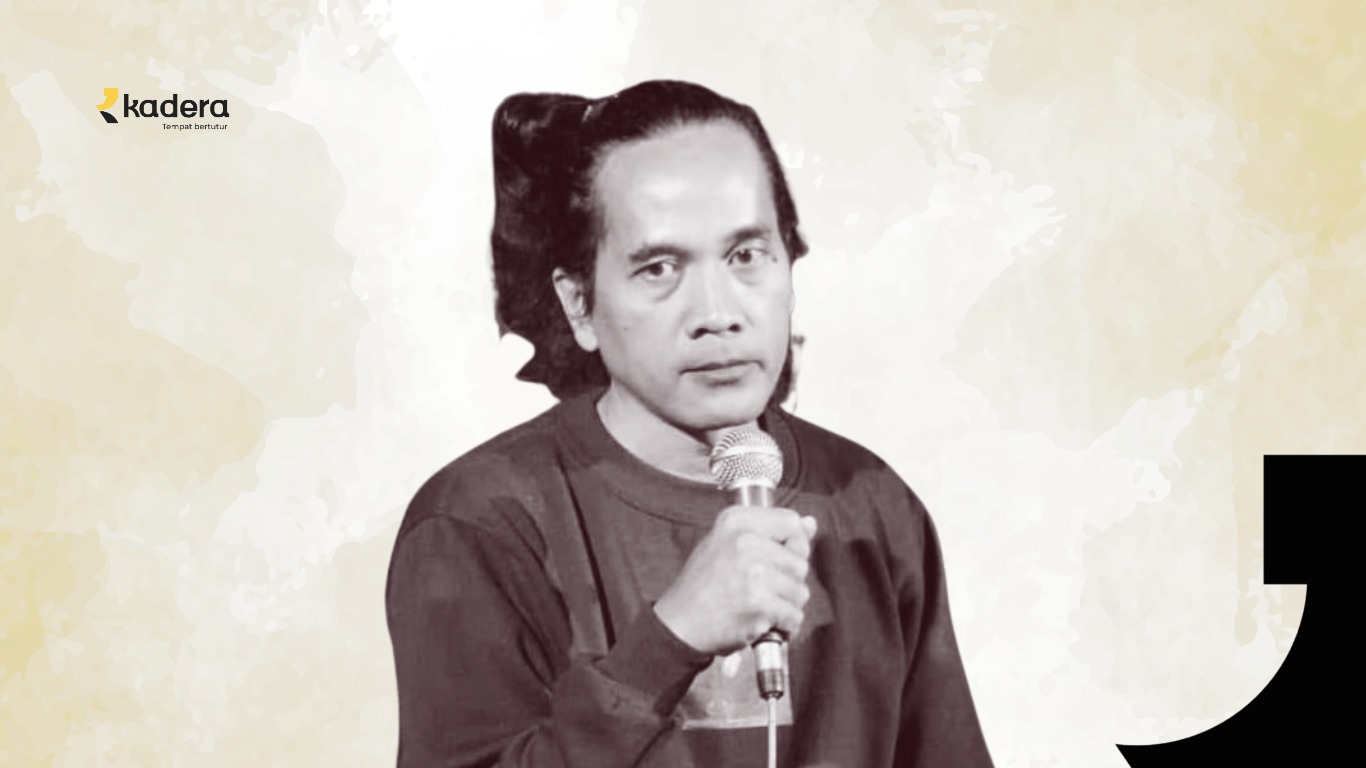
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.