DARI negeri yang jauh, kita mendapat cerita yang memukau. Cerita yang meminta imajinasi, bukan kecerewetan yang sia-sia: “Lampu kuning menyala…Para pengendara mobil menahan kakinya yang tak sabar pada kopling, membiarkan mobil mereka siap siaga, maju, mundur, serupa kuda yang mampu mengendus kelebat cambuk yang segera disabetkan. Para pejalan kaki baru selesai menyebrang tapi nyala lampu yang membolehkan mobil-mobil melaju akan tertunda beberapa detik. Sejumlah orang bersikeras bahwa penundaan ini, meski tampaknya amat sepele, hanya perlu dilipatgandakan oleh ribuan lampu pengatur lalu lintas yang ada di kota dan perubahan berturut-turut warnanya untuk menghasilkan salah satu penyebab paling serius terjadinya kemacetan lalu lintas.”
Kita tidak sedang membaca penggalan cerita yang berlatar di kota-kota yang masuk dalam peta Indonesia. Yang menulis cerita bernama Jose Saramago. Ia membuka ceritanya dengan jalan dan mobil sebelum kejadian yang dahsyat: kebutaan. Petikan dari novel berjudul Blindness. Kita jangan menyepelekan masalah jalan dan mobil yang ditulis oleh peraih Nobel Sastra 1998. Ia tidak bermaksud membesar-besarkan masalah mobil di dunia tapi pembaca dibujuk agar senewen dengan kota-kota yang makin dikuasai mobil. Bagaimana mobil bisa menyesaki dunia dan menimbulkan petaka yang tidak habis-habisnya?
Jawaban sedikit ada di Indonesia. Beberapa hari yang lalu, orang-orang ribut dan membuat perlawanan di jalan. Mereka jengkel dengan para pejabat yang naik mobil mewah. Mobil itu mendapat pengawalan dan mencipta iring-iringan di jalan yang sedang sibuk dan ramai. Pejabat dalam mobil ingin lekas sampai alamat tujuan, yang mengharuskan mendapat maklum dari para pengguna jalan. Mobil pejabat yang didahulukan agar lancar, yang tampil menciptakan suara-suara yang penuh peringatan atau perintah: menghendaki mobil-mobil lain minggir atau menyingkir. Yang sedang kita gosipkan bukan berasal dari novel tapi bersumber jalan-jalan di Jakarta. Pemicunya adalah mobil pejabat dan aparat yang bertugas melayani pejabat.
Pejabat dan mobil itu cerita lama. Maksudnya, Indonesia memiliki cerita yang buruk, bukan cerita indah, bahagia, dan bertebaran kebaikan. Siapa ingin mengenang mobil, pejabat, dan kekuasaan? Bukalah buku berjudul Tirani dan Benteng (1993) yang berisi puisi-puisi gubahan Taufiq Ismail. Kita sedang malas membaca puisi. Yang diperlukan adalah melihat halaman-halaman buku yang memuat foto-foto lawas (hitam-putih) berlatar 1960-an.
Kita melihat foto mobil bagus dari para pejabat yang sedang dilawan dan dimusuhi kaum demonstran. Pejabat pada masa kekuasaan Soekarno ditampilkan pamer kemewahan. Mereka adalah kaum bermobil yang angkuh dan memeras rakyat. Ada lagi foto-foto yang menampilkan para mahasiswa menduduki mobil, yang mengartikan mereka “menguasai” atau “menyita” mobil para pejabat. Mereka berteriak dan bersenandung melawan rezim Soekarno. Mobil dijadikan tanda atas kehancuran Indonesia dan hasrat mengubah Indonesia menjadi “baru”.
Akhirnya, para tokoh mahasiswa yang berada di barisan depan dan meluapkan kemarahan melawan kekuasaan masuk dalam pemerintahan baru. Mereka mendapat jabatan. Di mata publik, mereka gantian menjadi kaum bermobil. Yang semula menjadi kaum demonstran menjadi kaum yang turut membentuk rezim Orde Baru. Mereka tidak pantas naik sepeda onthel atau sepeda motor, Yang terbaik adalah berada dalam mobil demi menunaikan tugas-tugas negara dan pamer “kesuksesan” yang justru menghina rakyat.
Apakah cerita mobil di Indonesia sudah selesai? Yakinlah bahwa masalah mobil di Indonesia lebih gawat dibandingkan petikan cerita dalam novel yang digubah Jose Saramago. Sejak lama, masalah korupsi di Indonesia biasanya ada mobilnya. Kita saja yang malas menghitung jumlah mobil dan pola korupsi di Indonesia. Beberapa hari yang lalu, kita masih mengingat mobil-mobil yang dikoleksi tokoh cakap omong yang berada dalam kabinet Prabowo-Gibran. Ia berurusan dengan KPK. Yang terlihat di televisi adalah koleksi mobilnya dibawa dan diparkir di depan kantor KPK. Kita melihatnya terpukau! Mobil ceritanya melulu buruk dan bikin marah.
Yang buruk bukan sekadar di Indonesia. Di negara tetangga, demonstrasi digelar dengan tuntutan yang lugas. Mereka marah dengan para pejabat yang keseringan membeli mobil baru. Para pejabat menjadi kolektor, yang nalarnya adalah pamer dan bersaing. Artinya, di pelbagai negara, mobil tidak dijamin menimbulkan kehormatan tapi menguak aib-aib.
Kita sebenarnya ingin berimajinasi mobil melalui novel dan puisi saja tapi segala berita telah menghinakan Indonesia. Yang terbaru, kita ikut kecewa dan mendapat hiburan buruk masih bersumber mobil. Konon, ada murid yang membawa mobil ke sekolah, Teguran diberikan oleh kepala sekolah. Murid itu punya bapak yang sedang berkuasa. Akibatnya, penguasa di situ marah kepada kepala sekolah. Kita tidak sedang mengusut kebenaran atau kesalahan berita. Yang terpenting: mobil itu momok dan malapetaka.
Pada abad XXI, mobil makin berkuasa di dunia. Yang berkuasa pun mementingkan mobil untuk pemenuhan hasrat dan kesombongan tak terbatas. Yang memusingkan adalah mereka bangga dengan koleksi mobil, bukan sadar diri dengan koleksi kebenaran, ketulusan, kesetiaan, dan kebahagiaan.
Siapa yang bisa memberi seruan agar mobil-mobil di Indonesia bercerita kedermawanan, kejujuran, keimanan, dan kemuliaan? Yang kita terima dari berita-berita sering bikin putus asa. Padahal, mobil belum mau punah di Indonesia, berarti keburukan-keburukan tak lekas sirna di Indonesia.
Kita putus asa saja dan mencari hiburan dengan menonton film di televisi. Film yang disukai anak-anak, yang menampilkan mobil-mobil yang bisa bicara. Hiburan itu menakjubkan ketimbang kita selalu dirundung derita akibat mobil-mobil di Indonesia, dari masa ke masa.
Penulis merupakan pengarsip, esais, dan kritikus sastra Indonesia

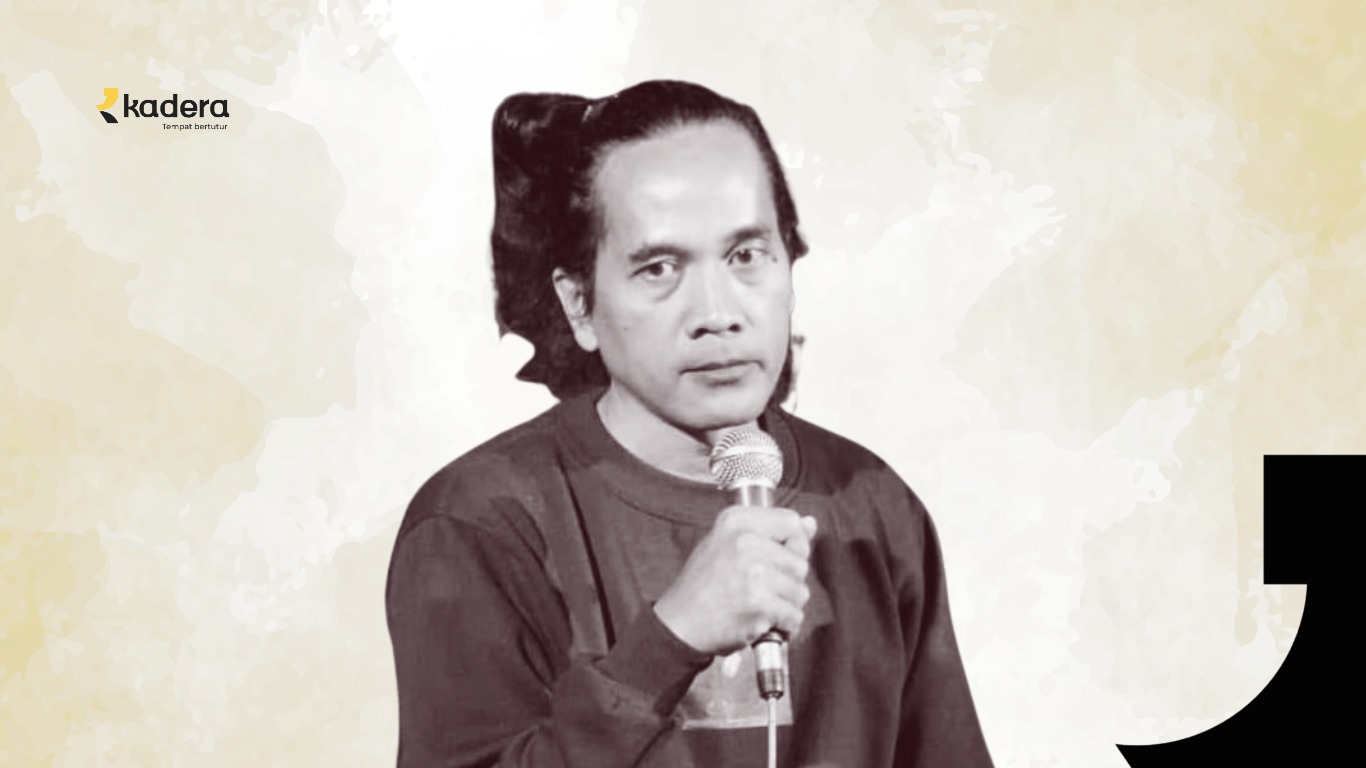
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.