Pada tahun-tahun yang rumit, orang-orang bakal susah memberi jawaban yang (paling) benar mengenai Indonesia. Apa masalah terbesar di Indonesia? Sekian orang agak meragu memberi jawaban: makanan, pajak, sawit, genteng, pena, atau polisi. Jawaban-jawaban yang sulit benar saat dinilaikan kepada penguasa dan pihak-pihak yang berkepentingan. Indonesia telanjur diangankan (berhasil) makmur, maju, moncer, dan bahagia.
Kita diminta mufakat terhadap kebijakan-kebijakan rezim Prabowo-Gibran. Namun, usaha memberi bantahan atau gugatan gampang menghasilkan bingung dan kecewa. Konon, beragam kebijakan itu bertujuan membentuk Indonesia yang mulia.
Akhirnya, kita lelah bila membuat daftar keraguan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Sekian hari lalu, lelah bercampur sedih saat kita mendapatkan berita dari NTT: 29 Januari 2026. Berita yang memuat masalah anak, kemiskinan, sekolah, pena, buku tulis, dan kematian. Bocah yang memilih pamit dari keluarga, sekolah, dan dunia. Kematiannya meninggalkan pesan.
Berita itu seolah “kebalikan” dari tepuk tangan atas capaian-capaian kebijakan akbar di Indonesia. Kita tak cukup menangis. Ingatlah, Indonesia tak cuma politik dan kemenangan yang berdalil demokrasi. Selembar kertas berisi kata-kata buatan bocah menguak sengsara jarang diributkan di istana dan parlemen.
Berita yang belum basi. Beberapa hari yang lalu, mahasiswa di UGM menulis dan mengirim surat kepada UNICEF. Pastinya surat itu berbahasa Inggris. Suara dari para mahasiswa justru memicu perdebatan di Indonesia. Yang paling sengit mengenai penggunaan diksi untuk sosok penguasa. Artinya, kita tidak boleh melupakan tanda seru yang diberikan bocah di NTT.
Kini, Indonesia memiliki halaman-halaman yang meragukan berkaitan capaian tujuan pendidikan nasional. Pada masa Orde Baru, setumpuk janji gagal diwujudkan. Warisan dari situasi 1998 belum memungkinkan pendidikan menjadi titik yang terbesar dalam mencipta kemuliaan Indonesia.
Di pelbagai kebijakan, kita terbiasa mendapatkan berita kelemahan kurikulum, album korupsi, dan gegeran buku pelajaran. Pada akhirnya, kita mengetahui pendidikan bertema besar makan, bukan pena dan buku tulis. Pada 1998, Agus R Sarjono menggubah “Sajak Palsu”. Kita masih bisa membacanya bermaksud mengenang episode setelah keruntuhan rezim Orde Baru.
Ia menulis kritik yang mengandung kelakar parah: Selamat pagi, pak, selamat pagi, bu, ucap anak sekolah/ dengan senyuman palsu. Lalu mereka pun belajar/ sejarah palsu dari buku-buku palsu. Di akhir sekolah/ mereka terperangah melihat hamparan nilai mereka/ yang palsu. Larik-larik untuk masa lalu. Apakah itu membuat kita turut menginsafi lakon pendidikan di Indonesia sering ilusif dan manipulatif? Pendidikan terlalu bermasalah meski sering menjadi perhatian besar oleh para penguasa.
Di NTT, bocah gagal merampungkan jenjang pendidikan dasar. Pendidikan yang belum mengundang kebahagiaan. Ia bertumbuh dalam keluarga yang miskin. Pendidikan menjadi seribu tanda seru, diawali alat tulis dan kemungkinan menikmati ilmu-ilmu. Bocah itu menunjukkan “keaslian” tragedi-tragedi pendidikan di Indonesia, dari masa ke masa. Ia seolah menanggapi pembesaran kepalsuan pendidikan di seantero Indonesia.
Dulu, puisi sebagai dokumentasi buatan Agus R Sarjono memberi peringatan: Lalu orang-orang palsu/ meneriakkan kegembiraan palsu dan mendebatkan/ gagasan-gagasan palsu di tengah seminar/ dan dialog-dialog palsu menyambut tibanya/ demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring/ dan palsu.
Pada masa sekarang, kita mungkin belum perlu mengulangi diksi palsu. Kita berada dalam situasi rumit, yang meminta pertanggungjawaban demokrasi. Namun, satu bocah di NTT membuat kita mengaku salah dalam menggerakkan dan mengartikan demokrasi. Kita pun picik untuk membenarkan pendidikan itu sumber kemajuan dan kebahagiaan.
Kita berpindah dulu agar tak terjerat berpikiran melulu Indonesia. Di China, kita menemukan bocah yang bernama Ma Yan. Ia pun hidup dalam keluarga yang miskin dan birokrasi yang penuh kekacauan dan ancaman. Pertemuan kita dengan bocah itu melalui buku yang berjudul Ma Yan (2011) garapan Sanie B Kuncoro.
Ma Yan lahir pada 6 Maret 1988. Kita mengimajinasikan China yang sedang menanggung dampak-dampak besar impian Mao Zedong. Pendidikan yang terkena petaka-petaka. Ma Yan sadar dalam kubangan kemiskinan dan berharap pendidikan memicu perubahan nasibnya. Keinginan yang tidak mudah diwujudkan tanpa keajaiban.
Benda yang penting dalam hidup: pulpen. Benda yang sejtinya diperoleh dengan pengorbanan. Upah bapak sangat kecil. Di keseharian, uang sakunya sangat terbatas. Ma Yan mengerti harga pulpen itu terjangkau bagi orang lain. Namun, di jeratan kemiskinan, berhasil membeli pulpen membutuhkan tanggung jawab yang besar. Ma Yan rajin belajar sambil mengartikan pendidikan adalah album benda dalam raihan ilmu-ilmu. Pulpen (pena) dan buku tulis diwajibkan ada saat murid-murid belajar. Papan tulis dan buku pelajaran memberi kepastian berilmu.
“Kupertaruhkan pulpen itu demi nama baik bapak,” pengakuan Ma Yan. Ia seperti melihat nasib dalam pulpen. Pada saat digunakan untuk belajar atau membuat cerita harian, ia paham pulpen memiliki harga dan batas pemakaian. Di buku tulis, ia tidak mau main-main untuk pembuktian berilmu sambil mengangankan masa depannya. Hidup di desa yang sangat kesulitan air dan kutukan kemiskinan perlahan ditafsirkan melalui pulpen. Ma Yan sadar diri sebagai anak perempuan yang sulit menjamin kebahagiaan keluarga pada masa depan.
Renungan terbaca dalam pengisahan Sanie B Kuncoro mengenai kehidupan Ma Yan sebagai bocah: “Alat tulis dan anak sekolah adalah paduan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap murid sekolah selalu memerlukan alat tulis dalam proses belajarnya. Pena adalah salah satu alat-alat tulis itu. Tapi tidak setiap murid sekolah beruntung atau mudah mendapatkan alat-alat tulis itu. Langit tidak cukup baik hati sehingga menumpahkan alat-alat tulis dari jendela langit.”
Kita mengetahui nasib bocah di China. Ia menginginkan pena dengan segala kesulitan dan pengorbanan. Pada saat pena di tangan, ia memenuhi hasrat pengetahuannya. Ma Yan pun mengisahkan diri melalui lembaran-lembaran kertas yang bergaris. Lakon itu mencari sejati, bukan kepalsuan. Ma Yan menganggap pendidikan menentukan masa depan. Kemiskinan dan kelaparan setiap hari ditebus dengan pena agar segala hal bisa dibahasakan kepada dunia.
Pada abad XXI, pena tetap masalah. Di Indonesia, kepemilikan pena atau alat tulis belum merata. Di NTT, bocah memberi tanda seru terbesar tentang pendidikan. Kemiskinannya mengabsenkan pensil dan buku tulis. Ketiadaan yang menimbulkan penderitaan saat ingin berilmu.
Ia berada dalam situasi yang pelik. Pada saat berkuasa, Joko Widodo sering membagi buku tulis.
Kini, bocah itu hidup dalam rezim berbeda meski Gibran kadang masih membagi buku tulis. Kita menduga Gibran tidak sampai ke desanya di NTT untuk memberikan buku tulis. Bocah memilih kematian itu belum beruntung. Bocah tidak perlu menulis masalah demokrasi dan kapitalisme di selembar kertas. Ia sekadar mencantumkan kata-kata sederhana untuk membuka tabir kepalsuan-kepalsuan di Indonesia.
*) Kabut merupakan nama pena dari seorang pengarsip, esai, dan kritikus sastra Indonesia

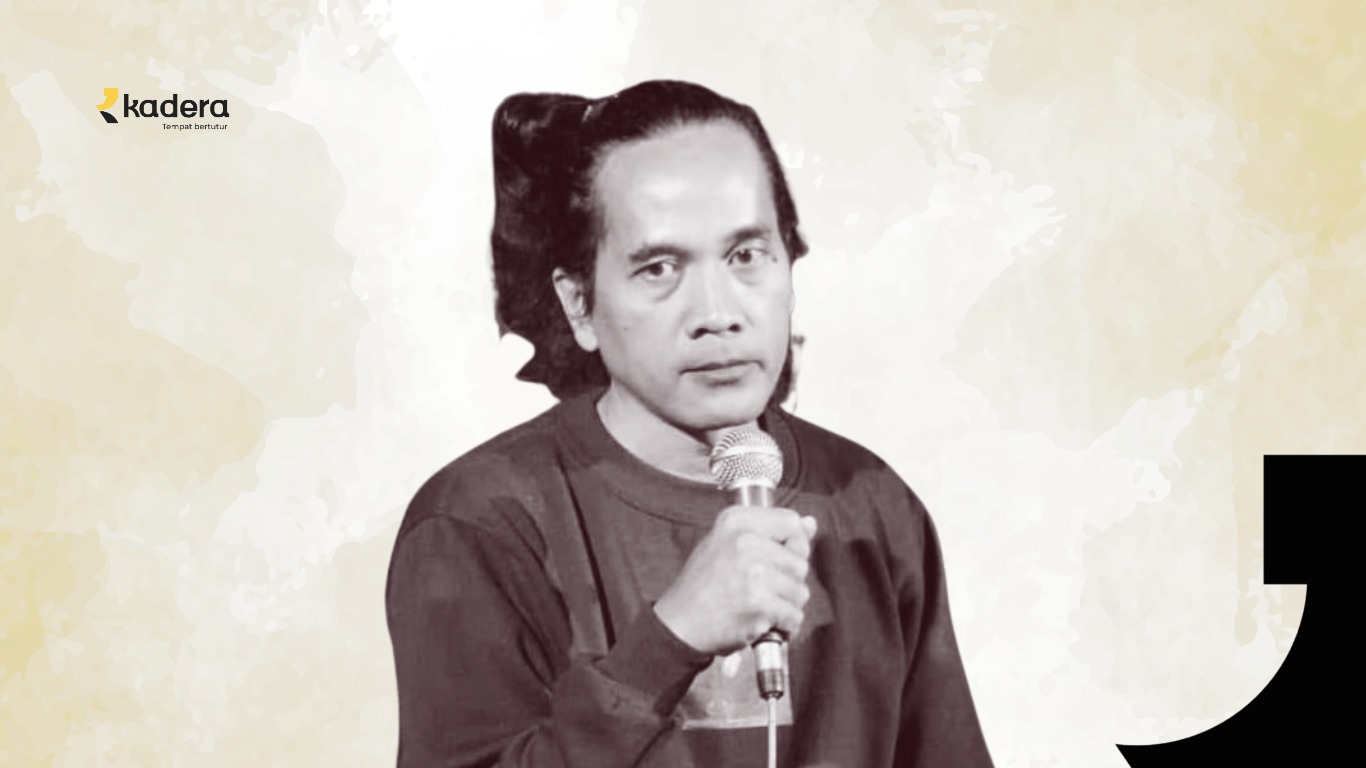
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.