KETIKA Syawal tiba, umat Islam telah berada di depan gerbang Ramadan, bulan yang di dalamnya terkandung berjuta-juta kemuliaan. Ramadan menanggalkan banyak fakta sejarah yang menjadi titik tolak peradaban Islam. Kitab peradaban dunia, Al Qur’an, mulai diturunkan kepada Rasulullah SAW, setelah melewati dua proses Nuzulul Qur’an, yakni ke Lauhul Mahfudz dan ke Baitul Izzah. Dalam studi Al Qur’an, proses-proses tersebut berlangsung di dalam bulan Ramadan pula.
Namun tulisan ini bukan dialamatkan pada pembahasan mengenai Al Qur’an secara komprehensif, melainkan pesan-pesan yang spesifik menyangkut Ramadan dengan ragam perintah dan dinamikanya; puasa. Karena sadar atau tidak, Ramadan yang disyariatkan puasa bersamanya, menjadi suatu topik kajian untuk melihat sebuah paradoks sosial masyarakat Islam. Lalu apa dan bagaimana seharusnya berpuasa?
Sepenggal Asrar Ash-Shaum
Seperti diuraikan sebelumnya, Ramadan memperlihatkan dirinya bukan sekadar bulan di dalam kalender hijriyah, melainkan fase historis yang berulang-ulang yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam. Bulan Ramadan seolah menavigasi dan memfasilitasi kita dalam kerangka teologi Islam untuk mendekatkan diri lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puasa selama sebulan, tarawih dan ritual peribadatan lainnya menjadi rekonstruksi atas jiwa, akal dan budi pekerti.
Tentang puasa, Imam Al Ghazali menjelaskan dengan gamblang dalam kitab Asrar Ash-Shaum (percikan kitab Ihya ‘Ulumuddin), bahwa ada tiga peringkat puasa; yakni puasa yang umum, puasa khusus, dan puasa yang terkhusus dari yang khusus.
Puasa yang umum ialah menahan diri dari nafsu makan dan nafsu seksual, seperti telah dijelaskan. Adapun puasa khusus ialah, di samping hal-hal di atas, menahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki, serta seluruh anggota badan dari melakukan sesuatu yang mendatangkan dosa. Adapun puasa yang terkhusus di antara yang khusus, di samping hal-hal tersebut di atas, ialah puasanya hati dari niatan-niatan yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi serta memalingkan diri—secara keseluruhan—dari segala suatu selain Allah Swt.
Pembagian puasa oleh Al Ghazali ini seakan memberi warning kepada kita kalau ada tingkatan-tingkatan yang berhubungan satu sama lain, sehingga puasa menjadi amalan yang mempunyai basic tersendiri. Ianya perlu dipahami secara metodologis karena terpolarisasi dengan ibadah-ibadah yang lain. Sederhananya, puasa harus dimaknai revolusi diri yang mencakup emotional, spiritual dan quotient dalam bahasa Ary Ginanjar Agustian.
Ramadan seyogyanya hadir membuka pintu hati bagi siapa saja yang sedang dan akan menempuh jalan menuju Tuhan. Al Ghazali mengatakan, puasa tidak ada yang dapat melihatnya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebab, ia adalah amal dalam batin seseorang, dilaksanakan hanya dengan kesabaran semata-mata.
Oleh sebabnya, objek vital Ramadan menitikberatkan pada masing- masing pribadi yang berupa wadah potensial menggali jauh kedalam diri, karena amalan-amalan di bulan Ramadan laksana puasa, dipandang sebagai sesuatu yang kuat dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Riwayat hadits oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sekiranya bukan karena setan-setan yang selalu mengitari hati manusia, niscaya manusia akan mampu memandangi kerajaan langit-langit.”
Dari segi inilah puasa dimisalkan sebagai pintu ibadah dan juga sebagai pagar penjaga keamanan hati manusia. Tentu saja sesuatu yang demikian itu sangat berkaitan dengan usaha dan kerja keras manusia.
Menurut Al Ghazali, mengingat puasa adalah perbuatan yang—secara khusus—mengandung penghinaan dengan paksa terhadap setan, dan juga sebagai upaya menyumbat salurannya atau mempersempit tempat mengalirnya, maka puasa sudah sepatutnya memperoleh kemuliaan penisbatan kepada Dzat Allah Swt.
Keutamaan Ramadan tak bisa dihitung, tak dapat dipilah secara matematik, apalagi yang dilihat nilai pahalanya. Cukup ibadah puasa, telah mengajarkan dan memberi banyak sekali pembelajaran jasmani dan rohani (fisik dan jiwa). Betapa banyak pendapatan ruhaniah yang didapatkan oleh orang yang berpuasa; pahala berlipat ganda, sehat pula. Namun bukan berarti kita mengkalkulatori setiap pengamalan yang dijalankan atau membuat tabel daftar pahala dari item-item perintah dan larangan Tuhan.
Meskipun demikian, Ramadan seringkali disalah-tafsirkan, yang mana Ramadan adalah ruang sangat progresif untuk menekan tingkat konsumsi— objektivasi nilai-nilai puasa, tetapi berbanding terbalik dengan realitas yang disaksikan. Bagaimana melihat Ramadan dari sudut pandang lain, yang berkorelasi dengan dinamika masyarakat Islam?
Sisi Lain Ramadan
Siapa yang bisa menahan lajunya globalisasi? Dunia yang tak lagi ada sekat. Pasar tidak bertumpu pada satu tempat, tapi sudah memenuhi sendi- sendi kehidupan. Tak selamanya Anda berada dalam situasi yang sama ketika harus berhadapan dengan gaya hidup yang mungkin kapan saja berubah. Apalagi jika telah terpapar dan terpenjara oleh konsumerisme.
Dalam konteks Ramadan, tak bisa dipungkiri kita akan menyaksikan Ramadan ibarat arena pertarungan gaya hidup yang tidak substansial. Tidak sedikit orang terjun dan tenggelam di dalamnya, menjadi objek segmentasi pasar yang terikat dengan usaha mengeksistensi diri tanpa tahu bahwa hal demikian bukanlah sesuatu yang “wajib”.
Uraian ini kiranya diketengahkan sebagai paradigma yang reflektif-konstruktif, yakni melihat sisi lain Ramadan yang konkrit dan hidup di tengah-tengah masyarakat.
Contoh paling sederhana adalah buka puasa. Ketika Anda lebih menyukai buka puasa di restoran dengan menghabiskan ratusan hingga jutaan rupiah, mengisyaratkan adanya keinginan eksistensial dalam dinamika sosial. Akan tetapi, untuk menguatkan aktivitas konsumsi sebagai satu sistem nilai, dalil yang akan mengemuka adalah hubungan silaturahmi patut dirawat. Itu menjadi “persembunyian” yang sunyi sekaligus berisik.
Sunyi yang dimaksud adalah pelatarannya bernuansa Islam sehingga terlihat kalau hal itu lazim terjadi dalam tradisi bulan Ramadan. Dan berisik pada konteks tersebut menceritakan bahwa, budaya konsumtif telah tertancap hingga menyentuh aspek peribadatan yang diatur oleh Islam dalam ibadah puasa.
Kita bukan mengacuhkan persaudaraan, kebersamaan—ukhuwah— dengan berpandangan seperti seorang individualis, walaupun sebagian orang tidak setuju seperti itu karena dianggap menolak keakraban sosial. Hal yang persis sama bahwa kita tidak punya legitimasi apa-apa untuk membatasi orang lain yang membutuhkan ruang yang menurut mereka benar.
Ramadan seharusnya menjadi bulan penghematan—menahan diri, kerap menjelma gelaran festival konsumsi. Di pusat perbelanjaan dan belum lagi di telepon genggam, promosi “Spesial Ramadan” menggoda dengan diskon besar-besaran. Kita dengan kerelaan berdesak-desakan di mall, pertokoan, butik, restoran, dan sebagainya hanya untuk memperoleh kelas sosial tertentu.
Memang ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW, yang sabdanya diriwayatkan Al Baihaqi dan Al Hakim dari Hasan bin Ali, ia berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan kami pada dua hari raya agar memakai pakaian terbaik yang kami temukan. Imam Syafi’I juga bilang, aku senang dalam dua hari raya orang hendaknya keluar dengan baju terbaik yang ia temukan.
Letak problematikanya adalah kekeliruan memaknainya, namun tidak menutup kemungkinan frasa ‘pakaian terbaik’ dimaknai adalah pakaian baru dan bermerek. Sampai-sampai sering tidak merasa cukup, kita lalu mengumpulkan begitu banyak barang, menumpuknya, seolah ramadhan adalah ajang perburuan produksi.
Dalam istilah, saya biasa menyebutnya konsumen gampangan: adalah mengorbankan keintiman batin yang harusnya terjaga dan dikontrol oleh pikiran yang logis yang sebenarnya jadi salah satu output pendidikan puasa.
Seperti contoh diatas, bahwa kapitalis tidak tinggal diam dalam menyiasati setiap fenomena yang tumbuh di masyarakat meskipun komunitas masyarakat tertentu sedang dalam ritual keagamaan yang menjadi kewajiban umat beragama. Bukan lagi sesuatu yang absurd, perkembangan teknologi informasi selain menyuguhkan percepatan pengembangan tiap sektor, terdapat efek yang mempengaruhi kultur masyarakat.
Masyarakat disulap melalui rekayasa algoritma untuk menggeser kecenderungan naluriah yang berintensitas tinggi, menjadi sekumpulan robot yang bergerak sesuai tanda yang melintas di banyak platform media.
Bahwa berbagai fenomena yang muncul khususnya sehimpun nilai yang tergeser dari anjuran puasa. Alasan yang mendorong hal tersebut, argumentasi jika manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang membawanya menuju pada objek yang memberinya kepuasan. Seperti kata Jean Baudrillard dalam Masyarakat Konsumsi (2004), sistem kebutuhan adalah produk dari sistem produksi, bahwa kebutuhan tidak dibuat satu per satu dalam hubungan dengan objek-objek lain tetapi dibuat produksi sebagai kekuatan konsumtif.
Walaupun studi psikologi menjelaskan manusia akan mengejar apa-apa yang dibutuhkannya, kasus yang terjadi merupakan sebuah paradoks, bahwa berpuasa yang diperintahkan dan sudah diterangkan dalam kitab suci, kitab hadits dan tafsir, seakan-akan hilang manakala Ramadan tiba.
Mencermati ini semua, apakah substansi dan nilai-nilai puasa justru berpotensi mengalami pergeseran?

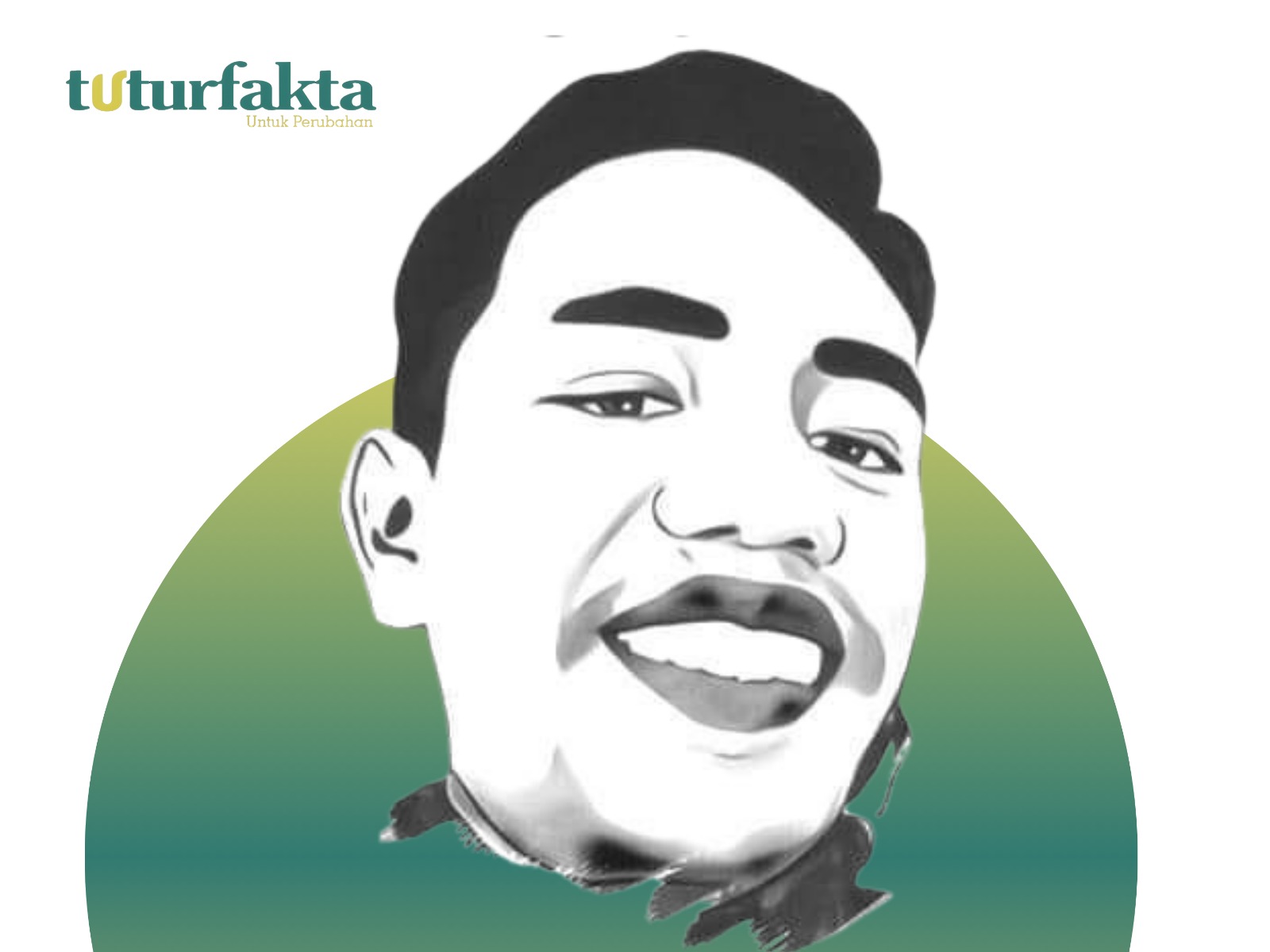
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.