YANG ditonton adalah perang. Di tempat-tempat yang jauh, para penonton perang merasa mendapat “hiburan”. Di depan matanya, perang adalah tayangan yang sering langit, sebelum kehancuran bangunan-bangunan yang semula tegak dan kokoh. Perang dilihat berlatar langit: pemandangan yang memukau. Mereka menonton selama gawai terbuka dan menyala. Perang di genggaman tangan. Perang di layar yang kecil.
Penonton ingin perang itu panjang. Namun, gelaran perang cuma belasan hari. Ada banyak argumentasi yang bertabrakan. Para pengulas argumentasi yang cepat berakibat gampang membuat konklusi. Yang sempat menonton merasa perang belum sampai puncaknya. Perang di tahun 2025 yang cepat berakhir bikin kecewa. Padahal, ada yang lega atas nama perdamaian dunia. Ada yang ingin mengetahui pemenangnya.
Perang yang kemarin masih banyak penontonnya. Selama berhari-hari, ribuan atau jutaan orang ketagihan perang. Mereka tidak (sempat) berimajinasi tapi tergesa mengikuti segala tontonan yang mengandung “kebohongan”. Tontonan “picisan” yang telanjur diobrolkan di rumah, warung, tempat ibadah, pasar, dan sekolah. Perang yang tontonan dalam gawai melebihi pengalaman orang-orang mengikuti perang melalui layar televisi, puluhan tahun yang lalu.
Mereka yang bertumbuh dalam dongeng memilih tidak menjadi penonton. Perang yang menjadikan rudal sebagai keunggulan dianggap tidak menyihir jika dibandingkan perang-perang yang terimajinasikan bersumber epos dan kitab suci. Yang selalu teringat perang-perang dalam buku sejarah bercampur dongeng mengetahui tokoh-tokoh hebat di Yunani, Romawi, Tiongkok, India, dan lain-lain. Perang mengharuskan munculnya tokoh-tokoh yang sakti. Yang ajaib menjadikan perang patut dihayati.
Pada masa lalu, perang adalah sumber pengajaran yang menyatakan kebaikan, keberanian, keadilan, dan keikhalasan. Semua itu terbuktikan jika ada kecurangan, kebengisan, dan kesombongan. Maka, perang-perang yang selalu dituturkan atau dituliskan ulang akan merawat imajinasi yang tafsir-tafsirnya pasang dan surut mengikuti suasana zaman dan kesanggupan orang dalam mengolah bahasanya.
Yang rajin membaca kitab suci mengetahui bahwa Tuhan memberikan firman atau ajaran yang terbaca dalam perang-perang yang terjadi. Kitab suci yang memikat memiliki halaman-halaman mengenai perang. Para pembaca kadang merasakan ketakutan dalam mengikuti perang dalam kitab suci. Bagi yang tabah dan tenang dalam membuat konklusi, perang-perang dalam kitab suci menyibukkannya memikirkan yang suci. Perang untuk pembuktian iman. Perang adalah memihak dan menginginkan yang suci.
Di Indonesia, kita hidup dengan warisan cerita dan sejarah perang. Murid-murid di sekolah telanjur membayangkan perang, yang merangsangnya bermain perang-perangan. Namun, anak atau remaja yang tidak mudah terbujuk buku pelajaran sejarah memiliki imajinasi yang memukau saat menikmati novel-novel fantasi, yang berasal dari banyak negara diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Larisnya novel-novel fantasi “mengesahkan” perang itu “abadi”. Yang berlanjut menonton film berdasarkan novel fantasi terduga tidak menggubris lagi buku-buku pelajaran sejarah Indonesia atau pidato-pidato para pejabat yang mengaku paham sejarah.
Di luar tontonan perang di gawai dan manjurnya fantasi perang dalam novel-novel, beberapa orang pelan-pelan membaca buku sejarah yang berbobot. Sejarah yang tidak boleh dimengerti asal-asalan seperti saat mengikuti upacara atau mendengarkan omongan pejabat dalam seminar yang meragukan. Teringatlah buku berjudul Perang di Jalan Allah (1987) yang ditulis Ibrahim Alfian. Buku lawas yang kita agak sulit menemukan (lagi) di perpustakaan umum. Buku itu mungkin berada di kamar atau rumah yang dihuni pembaca mengalami masa 1980-an.
Sejarah adalah buku yang dibaca dalam waktu berjam-jam, sangat berbeda dengan penggunaan waktu oleh para penonton perang di gawai. Membaca itu kesungguhan dan ketabahan, yang membuka halaman-halaman perang hanya didukung dengan foto-foto berwarna hitam dan putih.
Yang ditulis Ibrahim Alfian adalah perang di Aceh, yang sengit pada abad XIX. Perang yang menimbulkan kagum atas keberanian orang-orang Aceh yang beragama Islam. Di pelbagi sumber, perang itu mengisahkan iman. Pasukan Aceh terbiasa mengumandangkan kalimat tauhid di medan perang. Mereka menyatakan sedang berperang dengan kaum kafir.
Ibrahim Alfian menyampaikan: “Peluru yang dimuntahkan mulut meriam Belanda pada 1873 ketika mendaratkan pasukannya di pantai ujung barat Nusantara adalah pencetus timbulnya perlawanan rakyat Aceh. Perang melawan Belanda itu bersifat defensif, jihad untuk mempertahankan diri.” Perang itu dipelajari bukan melalui tontonan seperti perang dalam abad XXI. Perang senantiasa menghasilkan gubahan sastra. Yang berperang kadang mendapatkan bekal sastra untuk raihan kemenangan. Maka, pembaca yang serius mencermati perang melanjutkan merampungkan buku yang berjudul Sastra Perang: Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Perang Sabil (1992) yang disusun Ibrahim Alfian.
Pembaca yang tidak mau mendapat bualan atau kebohongan melalui tontonan-tontonan perang di gawai masih memilih berhadapan dengan buku. Pembaca itu membuka buku yang berjudul Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 (2012) garapan Peter Carey. Buku yang menguak perang di Jawa abad XIX. Pembaca menemukan perang-perang di Nusantara, selain di Aceh.
“Perang Jawa (1825-1830) merupakan tonggak perubahan penting dalam sejarah Jawa dan seluruh Nusantar,” tulis Peter Carey. Perang-perang digelar di Nusantara. Para pembaca mengetahui perang-perang yang mendasarkan pada iman dan kekuasaan. Perang-perang yang selalu dicantumkan dalam buku sejarah atau buku pelajaran sejarah, yang nantinya membenarkan capaian Indonesia merdeka (1945). Yang membaca bermain ingatan melalui kalimat-kalimat dalam album foto lama. Pembaca buku membutuhkan waktu lama, mencari derajat pemaknaan yang melebihi hitungan menit untuk para penonton perang di gawai.
Penulis merupakan pengarsip, esais, dan kritikus sastra Indonesia*

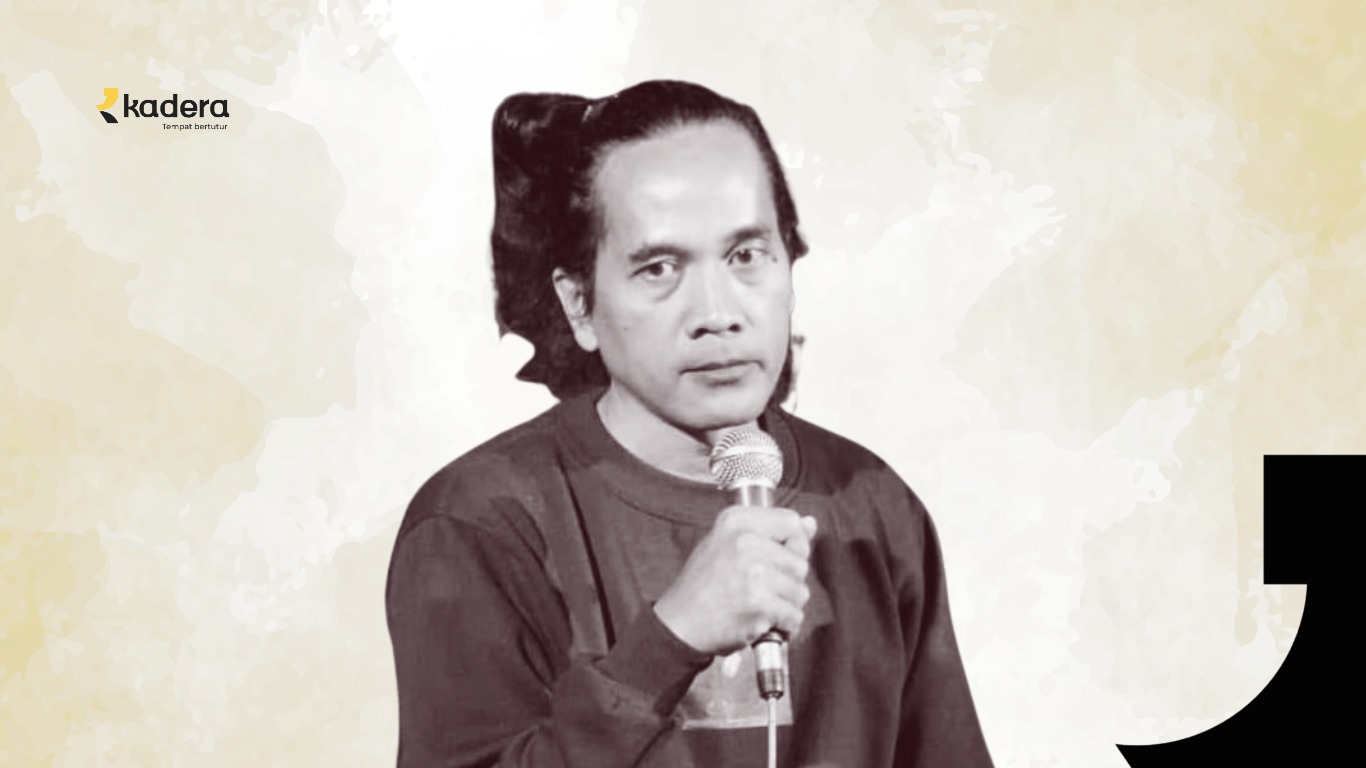
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.