HARI-HARI adalah tawa yang menyedihkan. Tawa disulut oleh satu orang yang berada di panggung. Yang terjadi adalah perayaan tawa ribuan orang. Mereka terhibur tapi ditantang untuk berpikir serius tentang Indonesia. Yang ditertawakan adalah masalah-masalah besar dan genting. Mengapa tertawa jutsru menghiburnya hanya sekejap tapi keseriusannya berlipat ganda?
Publik masih dibingungkan dampak-dampak Pandji P yang acaranya ditayangkan Netflix, yang berada dalam lakon komedi tapi mendapat reaksi pelbagai pihak yang menginginkan itu politis dan bermasalah hukum. Tawa yang dituduh berbahaya. Orang-orang yang sempat tertawa oleh Pandji mulai disuguhi kerancuan yang membesar.
Semula, tawa mengenai nafsu korupsi, birokrasi “menang-menangan”, ketokohan yang aneh, dan lain-lain, perlahan menjadi polemik. Artinya, tawa ditandingi kemarahan dan kebencian.
Kita berada dalam situasi yang absurd. Yang lucu itu politis. Namun, politik yang dicurigai macam-macam tidak mau dianggap “lucu”.
Kita melihat ada “pelarangan” lucu, yang berakibat perayaan hidup sebagai manusia Indonesia mengalami gangguan-gangguan. Indonesia seperti belum saatnya menjadi “tanah air kelucuan”. Yang terjadi adalah hari-hari yang menegangkan, yang memudahkan saling menyalahkan.
Hal-hal lucu tidak hanya berasal dari Pandji. Kita menemukan banyak kelucuan dari banyak sumber. Orang-orang boleh tertawa tapi batas-batas telah dibuat agar tawa bisa dipatuhkan oleh kekuasaan atau dibawa dalam urusan hukum. Jadi, pilihan untuk tertawa mengandung risiko.
Akhirnya, kita sulit membayangkan terwujudnya “mati ketawa cara Indonesia”. Kita menggunakan kata-kata itu berdasarkan buku yang pernah laris di Indonesia pada masa Orde Baru: Mati Ketawa Cara Rusia (1986), yang disunting oleh Z Dolgopolova. Buku edisi terjemahan bahasa Indonesia itu mendapat ribuan pembaca, yang mengandaikan kelucuan-kelucuan tercipta di Indonesia.
Buku kecil yang laris dan berdampak besar dipengaruhi tulisan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi pengantar atau pendahuluan bagi pembaca. Ingat, tawa yang dihasilkan melalui bacaan, bukan tontonan. Jadi, tulisan Gus Dur memiliki peran penting untuk mengajak orang-orang menyadari tulisan yang bergelimang tawa atau tulisan mencipta tawa.
Gus Dur memuat lelucon sendiri, yang mungkin sempat membuat kikuk penerbit. Para pembaca berhak terhibur atau mengaku tidak puas setelah khatam buku kecil bereferensi Rusia. Yang disampaikan Gus Dur: “Kalau tidak puas, tentu tidak mungkin buku ini dikembalikan kepada penerbit, dengan ganti rugi. Itu tidak lucu sama sekali. Masih lebih lucu kalau para pembaca meloakkan saja buku ini, agar tidak tertawa seorang diri karena orang lain tidak mampu membacanya karena tidak mampu membelinya dengan harga asli.”
Bayangkan, tokoh yang diminta memberi kata pengantar malah ikut tampil memberi hiburan yang aneh. Konon, kehadiran pengantar dari tokoh tenar berdampak buku akan laris. Namun, Gus Dur membuat ajakan agar buku dijual ke pedagang buku bekas. Artinya, ada kebebasan dalam merayakan dan mengartikan tawa dari bacaan.
Lelucon yang sangat berbeda bila kita membandingkan dengan beragam pertunjukkan lucu atau humor di Indonesia abad XXI. Apakah saat masih muda Pandji pernah membaca buku berjudul Mati Ketawa Cara Rusia, yang memicunya berani dalam arus tawa di Indonesia?
Yang membuat kita sedih adalah perlawanan terhadap tawa. Ada pihak-pihak yang marah dan mendendam atas pertunjukkan Pandji. Ada yang saling bersengketa di media sosial mengikuti alur politik. Keributan rumit diadakan oleh pihak-pihak yang merasa berhak merecoki tawa di Indonesia. Yang mulai bermunculan adalah kemarahan-kemarahan, yang menempatkan pemberi lucu dalam kesalahan dan pelanggaran.
Kita sedang mengalami “zaman marah”. Apakah kita ikut marah agar lumrah? Apakah kita mengelak dari marah agar waras? Namun, usaha tidak marah dengan tertawa justru masalah besar. Tawa itu dimusuhi. Tawa yang dicurigai sengaja menghina, menyerang, dan menyingkap. Padahal, kita tidak harus selalau mengikuti kata-kata Pandji. Apa-apa yang disampaikannya adalah hal-hal yang sifatnya tidak rahasia atau terlalu mengejutkan bagi yang melek politik di Indonesia.
Mengapa tawa tidak lagi pembebasan? Di Indonesia, tawa mudah dituduh “kejahatan” yang mengganggu alur dan pamrih kekuasaan. Kita tidak ingin terjebak meributkannya saat terjadi upaya merendahkan dan membatasi humor. Yang patut dipikirkan selama seribu hari adalah tawa. Apakah tawa boleh disuburkan di Indonesia?
Kita tidak menanti jawab dari birokrasi, DPR, MK, atau partai politik. Penberi jawab yang berasal dari negeri jauh dapat dijadikan bekal. Yang menjawab bernama Henri Bergson. Kita membaca jawabannya melalui buku edisi terjemahan bahasa Indonesia yang berjudul Filosofi Tawa (2020).
Filosof itu mengungkapkan: “Tawa pastilah menjawab tuntutan-tuntutan kehidupan bersama. Tawa pasti mempunyai signifikasi sosial.” Dua kalimat cukup membuat kita merenung tentang tayangan Pandji dan konsekuensinya bagi penonton.
Konsekuensi yang paling telak ditanggungkan para tokoh dan institusi yang disebutnya di atas panggung. Kita sebenarnya mulai diajak memikirkan mereka yang disebutnya, tak lagi mengurusi Pandji. Yang menyebabkan berhitung dalam memberi perhatian adalah tawa.
Tawa yang menjawab. Di Indonesia, tawa malah mendapat pertanyaan-pertanyaan dan tuntutan-tuntutan. Kita mengaku lelah dengan keributan gara-gara tawa. Yang bikin jengkel adalah pihak-pihak yang mengumbar marah. Kita kepikiran bahwa tawa itu dosa?
Tawa pun melanggar konstitusi? Yang marah menyatakan segala kebenaran, yang misinya adalah “memusuhi” tawa. Publik dibikin bingung dan lelah agar menentukan sikap, memihak yang tertawa atau mengangguk kepada yang marah.
Mengapa orang-orang mudah marah? Mereka mungkin belum pernah membaca buku yang berjudul How to Keep Your Cool: Sebuah Panduan Klasik Mengelola Amarah (2021). Buku warisan dari Seneca, dari abad yang sangat jauh dari perayaan tawa dan penghamburan marah pada abad XXI. Buku kecil mengajak kita memikirkan lagi tentang marah, dari masa ke masa. Kita belum perlu melanjutkan renungan gara-gara mudahnya pejabat dan pihak-pihak menempel kekuasaan mudah marah.
Seneca yang bernasihat: “Kita akan mampu memastikan bahwa kita tidak menjadi marah jika meletakkan di hadapan mata semua keburukan yang bangkit oleh amarah dan menelitinya dengan cermat. Kita harus menuduh dan mengutuk amarah, membedah kejahatannya dan mengungkapnya secara terang-benderang, membandingkannya dengan kejahatan terburuk, sehingga kitab isa melihat dengan jelas, apakah amarah itu.”
Pada masa sekarang, kita sangat sulit menaham marah. Namun, kemarahan kita mudah dicaplok oleh kemarahan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan modal. Akhirnya, kita sungkan untuk marah tapi memilih tertawa. Padahal, tawa malah bisa dicap “kejahatan” bila kita gagal menikmati dengan ketulusan dan hasrat pembebasan.
Kabut merupakan nama pena dari seorang pengarsip, esais, dan kritikus sastra Indonesia

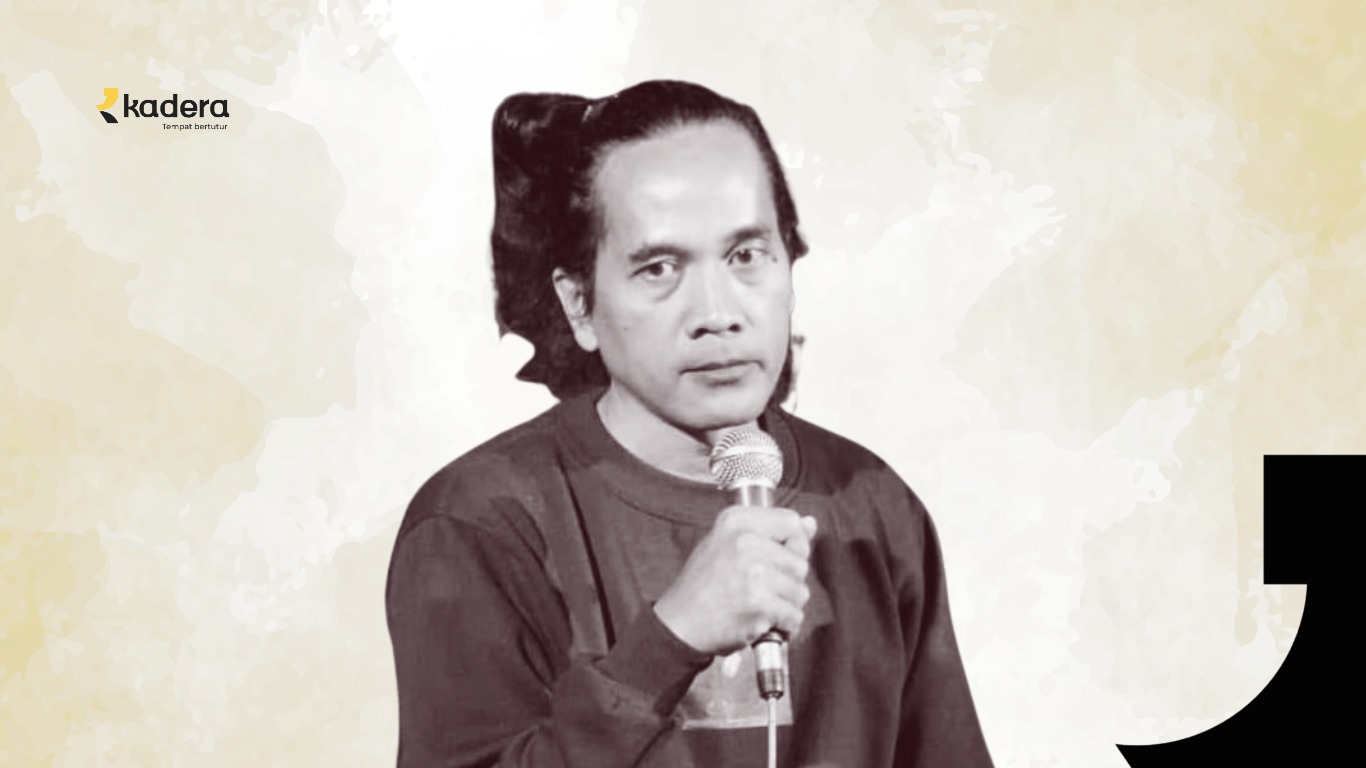
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.