YANG tertulis makin banyak. Siapa yang membaca? Kita sedang memuji serbuan tulisan di media sosial. Orang-orang keranjingan membuat tulisan (pendek atau panjang) di media sosial. Mereka sangat gampang mengetik huruf-huruf, tampil terbaca sebagai tulisan. Yang terbaca kadang salah ejaan atau tanda baca. Biarlah itu menjadi sejenis pameran yang tidak pernah rampung.
Apakah yang setiap hari menyajikan tulisan di media sosial adalah penulis? Kita boleh menyebutnya “penulis”. Maka, tulisan-tulisan yang dihasilkan selama bertahun-tahun dapat menjadi buku, tak perlu ada pembacanya. Yang terjadi memang arus tulisan yang membesar. Ada yang membaca dan meributkan tapi ada yang lekas berlalu tanpa mendapat “like” dan komentar satu kata saja.
Yang mau membaca pelbagai tulisan mengenai ijazah, penjambret, koruptor, makanan, sepakbola, selingkuh, atau polisi, belum dijamin mendapat pengesahan sebagai “pembaca”. Padahal, ia sudah merelakan waktu-waktunya untuk kata-kata yang bermunculan di media sosial, yang menggerakkan emosi dan tantangan “bertengkar”. Ada yang mengaku selektif memilih yang menimbulkan tawa dan kesombongan.
Kejadian setiap saat adalah tulisan-tulisan yang berseliweran mampu menggantikan peristiwa orang memegang buku atau membuka halaman-halaman buku. Yang mengaku tetap menikmati buku cetak pun tergoda mengumumkannya di media sosial.
Sejak bertahun-tahun lamanya, kita dibosankan oleh foto orang dan buku. Ada ribuan foto buku bersama minuman dan makanan. Buku pun bersekutu dengan rokok. Foto-foto buku seolah memastikan Indonesia belum mengalami kepunahan penulis dan pembaca. Yang kita lihat adalah foto, yang diberi keterangan-keterangan mungkin berdusta bahwa orang-orang “memuja buku”. Ribuan foto apik menimbulkan iri sekaligus cemooh.
Kita tinggalkan semua itu mumpung pengisahan pembaca (dan) buku masih bisa terlacak. Yang menjadi lacakan bukan foto-buku di media sosial tapi puisi-buku yang terkandung dalam khazanah sastra di Indonesia. Apakah membaca puisi bertema buku membuat kita tenteram? Maksudnya, buku-buku mendapatkan kemuliaan, tidak melulu dipotret dan mengalami pengeditan sebelum dipamerkan di media sosial.
Pada 2025, Abinaya Ghina Jamela menulis puisi berjudul “Ketika Aku Membaca Buku”. Yang terlihat hanya kata-kata, tiada gambar atau foto. Pembaca dibujuk berimajinasi tentang pembaca (dan) buku. Bocah itu mengisahkan: Tik tok tik tok bunyi detak jam/ seperti air menetes ke lantai/ dan aku membaca buku./ Buku tentang jantung, detaknya/ seperti kuda berlari. Kalau aku/ membuka halaman seperti telapak/ kaki bergoyang. Aku membacanya./ Ibu berdiri di belakangku, tegak/ terdiam. Ibu melihatku membaca buku./ Di buku ada kulit, darah, mata, gigi,/ rambut, hidung, dan otot. Kenapa aku/ suka membaca? Biar pintar seperti ibunda.
Puisi tidak menyebutkan judul buku. Yang terbaca adalah Abinaya memang gandrung buku. Ia tidak membiarkan pengalaman membaca buku cepat berlalu. Menaruh ingatan dalam puisi itu kebutuhan ketimbang ia meminta dipotret ibu, berlanjut memamerkan foto kepada publik agar dipuji sebagai pembaca buku.
Di hadapan puisi, kita tidak mendapat kelugasan pembaca dan buku. Kita membaca dengan tebakan meski larik akhir menguak misi Abinaya: mengaitkan buku dan ibu (bunda).
Kita berganti membaca puisi gubahan Joko Pinurbo (2003) yang berjudul “Buku”. Pengalaman tokoh yang menemukan buku lamanya, yang tersedia di kios buku bekas (loak). Jarak waktu ikut menentukan cara menanggapi buku. Kita yang membaca merasa buku menyimpan waktu.
Joko Pinurbo mengisahkan: Ah, buku itu tidak sanggup lagi memamerkan/ keangkuhannya. Seluruh halamannya sudah/ kuning kecoklat-coklatan. Bagian pinggirnya/ sudah geriwing digerogoti waktu. Foto/ pengranganya pun sudah pudar. Malang benar/ nasibmu, pengarang. Fotomu yang jelek/ kaupasang dengan penuh kebanggaan/ hanya untuk merana dan mungkin tak pernah/ digubris orang.
Kita ikut merasa melihat dan memegang buku bekas. Adegan itu tidak dipotret walau Joko Pimurbo memasalahkan foto pengarang di buku. Sekali lagi, kita membaca puisi, yang berbeda kesan ketimbang melihat foto orang dan buku di media sosial.
Kita masih terkesima puisi. Yang terbaca selanjutnya adalah puisi berjudul “Sajak Ini Kuberi Judul: Buku” yang ditulis Hasan Aspahani. Puisi yang apik, menggelitik, dan menyentuh. Di situ, ada judul buku-buku. Pembaca menemukan pengakuan-pengakuan yang tulus dan membingungkan. Namun, puisi itu melulu buku.
Kita membaca bait yang minta pengesahan: Waktu kecil, kalau ada orang bertanya, “Engkau/ mau menjadi apa?” Aku menjawab, “Mau jadi buku…”/ Dan tak pernah ada yang bisa mengerti// “Wah, bagus. Menjadi penulis buku itu hebat…”// Sesudah tua, masih juga ada yang bertanya/ “Apa keinginan anda yang belum tercapai?” Aku/ menjawab, “Menjadi sebuah buku…” Kengeyelan yang sulit dimengerti orang lain. Tokoh ingin menjadi buku, bukan penulis buku atau cukup sebagai pembaca buku.
Yang (paling) mengharukan adalah bagian akhir puisi. Kita membacanya pelan saja, boleh berulang. Larik-larik yang tidak minta air mata tapi ketulusan untuk mengerti. Yang ditulis Hasan Aspahani: Tetapi tidak ada yang bertanya/ kau hendak dimakamkan di mana?// Diam-diam aku sedang mempersiapkan/ sebuah kematian yang paling sempurna:/ dikuburkan di dalam buku. Engkau tahu? Buku akan hidup abadi. Tak mati-mati! Kita membaca bukan sebagai khayalan murahan. Yang ingin menjadi buku dan ingin dikuburkan dalam buku adalah sosok yang terhormat. Ia bukan sosok yang suka berpotret bareng buku dan mengumbarnya di media sosial. Sosok yang tidak berminat menghasilkan ratusan atau ribuan foto.
Kita membaca cuma tiga puisi. Yakinlah masih ada ratusan puisi mengenai buku, yang mampu membuat kita berlindung dari serbuan foto bertema buku, yang terbit setiap saat di media sosial. Kita tidak mengharamkan foto tapi memerlukan yang terbaca dengan segala ketakjuban dan kebingungan.
*) Kabut merupakan merupakan nama pena seorang pengarsip, esais, dan kritikus sastra Indonesia

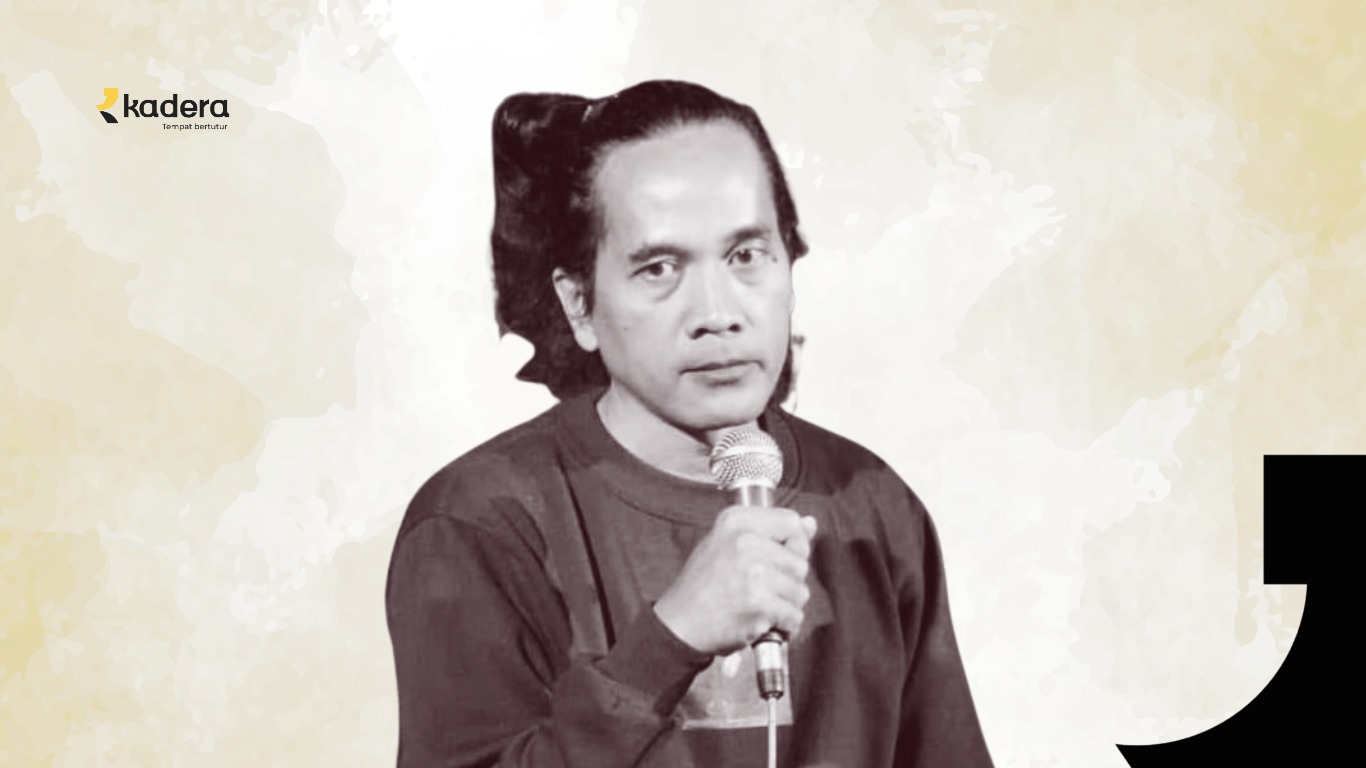
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.